IV. PENILAIAN ETIS
Pengantar
Bagian ini hendak menilai pem-belis-an dalam Gereja Sumba dari segi etika Kristen. Jadi, bukan suatu analisis mendetail tentang sumbangan kontekstual pada perkembangan gereja di Sumba dan tentang kristenisasi masyarakat Sumba. Sebab, analisis itu merupakan tugas penelitian sejarah gereja1 dan penelitian antro pologis tentang masyarakat Sumba. Penelitian ini bersifat praktis dan dengan tujuan menyajikan anjuran-anjuran etis yang akan tersaji dalam pasal 5.
Agar tujuan itu tercapai, kita perlu mengetahui bagai mana cara kerja Gereformeerde Zending. Kalau kita mengetahui pendidikan yang bagaimana yang telah diterima oleh masyarakat Sumba yang telah masuk Kristen, dan bagaimana reaksi mereka terhadap hal itu, barulah kita dapat belajar dari sejarah, untuk maju dan sampai pada tahap kontekstualisasi dan pengkristenan.
Mengenai pembagian pasal ini:Gereformeerde Zending telah mulai bekerja di Sumba sejak tahun 1881. Di antara penduduk yang berasal dari Sabu, ditemukan orang-orang yang telah menjadi Kristen. Karena itu, jemaat-je maat pertama yang mandiri pada tahun 1916 dan 1919 adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang Sabu. Jemaat-jemaat yang anggotanya berasal dari Sumba baru didirikan pada tahun 1930, 1932, dan 1937. Pendeta-pendeta Sumba yang pertama diteguhkan pada tahun 1942.2 Bagaimana ciri khas zending itu dan apa yang dikatakannya tentang pem-belis-an? Bagian 4.1 akan membahas pokok-po kok tersebut dalam rentang waktu antara tahun 1881-1936.
Pada tahun 30-an terjadi perpecahan gereja di Sumba Timur, dan pada tahun 50-an kembali terjadi perpecahan dalam salah satu dari kedua gereja yang telah terpecah itu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pokok permasalahan itu tergolong hal-hal asasi untuk sebuah gereja reformasi, dan apakah ada sangkut pautnya dengan pem-belis-an? Hal-hal tersebut terjadi dalam rentang waktu antara tahun 1936-1984 akan dibahas dalam Bagian 4.2, yang diakhiri dengan usul-usul penyederhanaan adat pem-belis-an, yang ditetapkan oleh salah satu Majelis Gereja dalam GGRI pada tahun 1984.
Bagian 4.3 membahas tentang kontekstualisasi dan peng kristenan, yang merupakan perkembangan-perkembang an universal dalam sejarah gereja, tidak terkecuali di Gereja Sumba. Apa arti dari ungkapan-ungkapan tersebut?
Bagian 4.4 membahas dasar-dasar penggunaan Alkitab dalam etika Kristen.
Bagian 4.5 merupakan pembelaan bagi kontekstualisasi dan kris tenisasi di Sumba.
1. Gereformeerde Zeneing ei Samba (1881-1936)
1.1. Gambaran Umum
Misionaris yang pertama adalah J.J. van Alphen, yang datang ke Sumba pada tahun 1881 sebagai utusan dari NGZV (Persekutuan Zending Reformasi asal Belanda). Persekutuan itu didukung oleh aliran-aliran ortodoks dalam Gereja Hervormd, dan sejak 1886 didukung juga oleh Nederduits Gereformeerde Kerken. Persekutuan itu kurang bertanggung jawab dalam pembinaan utusannya, itu sebabnya Van Alphen berpindah menjadi utusan dari Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK). Sejak tahun 1892, Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) bertanggung jawab atas zending ke Sumba, karena pada tahun tersebut Christelijke Gereformeerde Kerk dan Nederduits Gereformeerde Kerken bersatu menjadi Gereformeerde Kerken in Nederland.3
Pada tahun 1896, Gereformeerde Kerken itu bersidang dalam Sinode Umum di Middelburg dan memutuskan hal-hal penting tentang Zending. Th. Van den End mempermasalahkan apakah gereformeerde zending di Sumba itu benar-benar re formed adanya, sebagaimana pretensi sinode tersebut.4 Dasar-dasar Zending telah dirumuskan dalam 5 pokok, yang dua di antaranya berkaitan dengan pokok kontekstualisasi.
Sinode 1896 tentang pendirian gereja
Menurut Sinode 1896, tanda bahwa suatu gereja layak dise but mandiri adalah dengan diteguhkannya jabatan-jabatan. Tetapi, menurut Van den End, di Sumba peneguhan penatua memang sudah beberapa waktu lamanya dilakukan, meskipun peneguhan pendeta pertama baru dilaksanakan pada tahun 1942.5
Berbeda dengan perkembangan di Jawa Tengah bagian Selatan, yang juga merupakan wilayah gereformeerde zending. Menurut kami, sejarah gerakan Sadrach di Jawa Tengah mempercepatkan per kembangan menuju kemandirian dan menyadarkan para zendeling untuk tidak bersikap paternalistis. Van den End mengatakan: Sesudah kemandirian Gereja Kristen Sumba (GKS) pada tahun 1947, kaderisasi di Sumba dilakukan dalam waktu singkat, tetapi sayang karena terasa juga bahwa gereformeerde zending telah membentuk satu gereja yang kebarat-baratan di wilayah Sumba yang masih terbelakang itu.
Dari segi mutu pendidikan teologi, Sumba cukup maju, malah lebih dahulu dari wilayah zending lainnya.6 Tetapi, pen didikan terse but bertujuan khusus untuk mendidik guru Injil, sama seperti di Jawa Tengah. Persyaratan untuk jabatan pen deta sangat tinggi, sesuai dengan Sinode 1896, yang telah mengatur bahwa seorang misionaris harus seorang lulusan akademi teologi, dan persyaratan itu diberlakukan juga terhadap pendeta pribumi di Jawa dan di Sumba.7
Kemandirian dalam pandangan para misionaris tidak tergan tung pada kedewasaan rohani, tetapi dari kemampuan ekonomi jemaat untuk memelihara pemimpinnya.8 Menurut R.A. Webb, ke tegasan para zendeling dalam hal itu meng hambat perkembangan gereja di Sumba, tetapi Reenders menolak pandangan itu.9
Berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, adalah pendi rian F.D. Wellem, yang menekankan bahwa lembaga pengutus di Belanda mementingkan kemandirian, tetapi para zendeling meng anggap hal itu belum waktunya. Karena itu, mereka juga tidak mendukung ke arah kemandirian finansial dan juga tidak mendorong pemanggilan pendeta. Tetapi, mungkin lembaga pengutus itu lebih positif justru berdasarkan laporan para zendeling sendiri, yang menyampaikan jumlah yang cukup signifikan dari orang yang hadir pada perayaan Natal atau pada peristiwa pembaptisan. Sebenarnya banyaknya orang yang hadir itu hanya karena ikut meramaikan saja atau da tang karena mempunyai hubungan keluarga dengan orang Kristen. S.J.P. Goossens meng kritik penggambaran sepihak yang tidak seimbang itu. Pada saat yang sama para zendeling diberi informasi yang keliru melalui la poran-laporan para guru Injil, yang pada umumnya hanya menge mukakan hal-hal positif saja, sesuai dengan budaya Sumba.10
Sikap Sinode 1986 terhadap budaya
Satu pokok penting yang lain adalah visi Middelburg, yaitu agar budaya bangsa yang diinjili itu diberi peluang. Menurut Van den End, hanya sedikit dokumen tentang budaya Sumba yang ditemukan dalam arsip Zending Sumba, demikian juga tentang bagaimana sikap para misionaris dalam mendekati budaya itu.11 Berbagai majalah terbitan Zending memang menyinggung tentang budaya Sumba tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan inti budaya Sumba atau menganalisis nilai-nilainya yang dapat memberi man faat untuk penginjilan. Dalam hal ini Zending Hervormd, khususnya di Jawa Timur, lebih berbobot daripada yang dilakukan oleh Gereformeerde Zending di Sumba. Dalam hal ini, B. Schuurman telah menyusun sebuah dogmatika Jawa.12
A.A. Wessels dan kami juga, keberatan terhadap pembe daan yang dilakukan oleh Van den End antara zendeling gereformeerd dan rekan kerjanya dari Hervormd.13 Dalam Bab 2 dikutip karangankarangan dari D.K. Wielenga dan L. Onvlee. Van den End mengatakan bahwa Wielenga baru menulis tentang pemberitaan Injil sesudah dia meninggalkan Sumba dan mungkin karena ia bertemu dengan A.C. Kruyt di Tana Toraja yang sebe lumnya juga pernah mengunjungi Sumba. Menurut kami, masuk akal jika Wielenga dalambuku-bukunya menceritakan tentang bagaimana cara dia ber khotbah, dan bahwa buku-bukunya juga bersifat autobiografi.14 Isi karangan itu mirip dengan sum bangan K. Tanahomba dalam satu antologi tentang peka baran Injil Gereja Bebas tahun 1951.15
P.N. Holtrop juga membahas pokok tentang apakah zending di Sumba bekerja sesuai dengan pedoman Middelburg 1896 atau tidak.16 Pandangan H. Bergema yang dibahasnya, yang di dalamnya telah dia laporkan kepada Deputi Zending Sumba di Belanda tentang perpecahan gereja pada tahun 1938, dan memaparkan satu visi tentang sikap terhadap budaya.17 Holtrop mengemukakan pen dapat-pendapat yang berbeda dari para zendeling, seperti P.J. Lambooy dan L.P. Krijger, misalnya tentang memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dengan tepat Holtrop membuktikan bahwa keduanya mendasarkan pendiriannya atas ajaran A. Kuyper, yang merupakan ”bapa rohani” dari keputusan-keputusan Middelburg 1896. Sebab, Lambooy bertolak dari pan dangan Kuyper tentang ”anugerah umum” sedang Krijger bertolak dari pandangan Kuyper tentang antitesis. ”Anugerah umum” berarti karena kebaikan Tuhan maka dalam budaya-budaya juga terselip unsur yang baik, sehingga manusia dapat hidup di bumi ini. Sedangkan ”antitesis” mengutamakan pertentangan an tara agama Kristen dan agama-agama kafir. Menurut Krijger, adat adalah wujud nyata dari agama kafir.
Lambooy berpendirian bahwa prinsip-prinsip baru itu hendaknya bersinar dalam budaya lama yang kafir. Dia memberi peringatan terhadap pandangan Krijger, berd asarkan filsafat Kristen yang disebut Wijsbegeerte der Wetsidee, (filsafat tentang lingkungan hukum yang berbeda). Dalam pandangan Lambooy, ”lingkungan hukum iman bercampur dengan lingkungan-lingkungan hukum lainnya .... Mengenai bangsa-bangsa kafir juga harus kita bedakan antara lingkungan masing-masing itu .... Bagi orang kafir pun agama adalah agama, dan pergaulan sosial adalah pergaulan sosial”.18
A.A. Yewangoe mengingatkan tentang pendidikan yang telah diterima oleh ayahnya ketika mengikuti pendidikan di Sekolah Guru Injil di tempat Krijger mengajar. Menurut Yewangoe, pada umumnya para lulusan berfungsi baik, kare na: 1) mutu pendidikan, yang di dalamnya dipelajari bukan saja masalah-masalah gerejawi, melainkan juga pokok-pokok kemasyarakatan; 2) tingkat pemi kiran para siswa, yang sebe lumnya telah dididik menjadi guru sekolah; 3) asal para murid dan tingkat sosial. Menurut Yewangoe, tidak dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan itu kontekstuali sasi telah menjadi isu, tetapi tidak dapat disangkal juga bahwa pendeta Zending maupun pengerja Zending lainnya juga memperhatikan bahkan menghormati budaya Sumba. Hanya satu orang saja di antara para zendeling yang menentang budaya itu; yang dimaksud oleh Yewangoe adalah S.J.P. Goossens.19
H. Bergema menganggap bahwa budaya merupakan satu kesatuan. Sesudah masyarakat menerima Kristus maka budaya berubah total, sebab agama adalah inti budaya itu. Bergema berkehendak agar orang yang belum percaya kepa da Allah diperhadapkan dengan pokok inti ini, dan bukan dengan masalah-masalah adat secara khusus. Bergema eng gan melarang peraturan-peraturan adat tertentu, dia menginginkan agar orang Kristen pribumi diberi waktu untuk ber ubah. Sebab, jika mereka benar-bernar disentuh oleh Injil, maka seluruh kehidupan mereka akan diperbarui. Menurut
Holtrop, pandangan seperti yang dikemukakan Bergema ini tidak menghargai budaya, sebab menurut pandangan itu, budaya harus diubah oleh Injil.20 Pada akhirnya Holtrop memu tuskan untuk tidak setuju terhadap pandangan Bergema, demikian juga terhadap pandangan J.H. Bavinck, yang juga dikutip oleh Holtrop. Holtrop memang menyetujui pendirian mereka bahwa orang Sumba harus mendengarkan ”kabar baik”. Tetapi, dalam pan dangannya, hal itu agar mereka dapat mengartikan dengan lebih baik perubahanperubahan yang telah terjadi dalam masyarakat mereka. Perubahanperubahan tersebut telah mendapat tempat ”dalam sejarah tindakan Allah di dunia, yang telah diawali dengan penciptaan dan akan berakhir di Yerusalam baru, yang di dalamnya segala bangsa akan membawa harta dan kemuliaan mereka (...) Zending menghendaki lebih dari itu (dan juga lebih berpretensi), yaitu bahwa kepada orang-orang Sumba ditunjukkan di mana dan bagaimana seharusnya peralihan dari manusia lama ke manusia baru terjadi, yang tentangnya Alkitab terus-menerus menyatakan, yaitu hal itu adalah sebuah rahasia tentang ’nama baru’. Hal itu telah menjadi sejarah dan pengampunan akan diberikan kepada mereka yang dari hari ke hari mengalami peralihan dari kehidupan yang lama ke yang baru”.21
Dalam sebuah konferensi GGRI pada tahun 1987, yang membahas tentang adat, banyak orang Sumba dengan penuh sadar membedakan antara agama kafir dan aspek budaya Sumba lain nya. Menurut kami, pembedaan tersebut perlu dipertahankan, meskipun jelas bahwa bidang-bidang budaya tidak terlepas satu dengan yang lain.
Holtrop bersama dengan Jacqueline Vel mengemukakan pandangannya dalam retrospeksi terhadap sejarah Gereja Sumba ketika GKS telah mandiri selama setengah abad. Bahkan dia mengatakan bahwa terdapat satu Injil yang telah mendahului tiap budaya dan konteks (sesuai dengan pandangan L. Sanneh). Baik Injil, maupun budaya tidak bersifat kaku dan mati. Budaya merupakan sebuah proses berkelanjutan yang menyangkut hal ”mengartikan” dan ”diartikan”. Ciri khas Injil adalah ”dapat di terjemahkan”: pemberitaan yang tertua tentang penderitaan, ke matian, dan kebangkitan Yesus Kristus dikumandangkan dalam ruang-ruang ”budaya” dan dapat memberikan arti dan tujuan baru kepada masyarakat.22
Setengah abad sebelumnya, Bavinck dan Bergema berke yakinan bahwa hanya Kristuslah yang memberi kehidupan, karena itu seharusnya terbentuk suatu budaya yang sesuai dengan Kristus. Holtrop, seperti Bavinck dan Bergema, berpendapat bahwa budaya pada dasarnya adalah utuh dan di dalamnya agama menjadi pusat, tetapi Holtrop menghargai budaya tua dan agama suku. Di samping itu, Holtrop mencatat bahwa orang Sumba yang sudah menjadi Kristen telah terhisap ke dalam persekutuan sedunia yang baru, yaitu paraingu bidi dari gereja-gereja dan orang Kristen.
Sedangkan menurut F.D. Wellem, budaya dan agama membentuk kesatuan yang utuh. Sayang pen dapatnya itu tidak sejalan dengan pendirian Bavinck dan Bergema tentang perlunya membe dakan antara aga ma yang spesifik dan aspek-aspek lain dari kebudayaan.23
Wellem memberi corak pendirian D.K. Wielenga sebagai refor- med gaya klasik: seorang kafir yang terancam bahaya dan perlu diselamatkan. Tetapi, berbeda dengan zendeling-zendeling asal Eropa di daerah-daerah lain, Wielenga tidak dengan serta-merta membaptiskan orang. Menurutnya, iman harus tumbuh dan tidak dapat dipaksakan. Ketika kembali ke Belanda, orang yang telah dia baptis tidak banyak, tetapi dia mempunyai relasi yang baik dengan banyak orang Sumba (F.D. Wellem, hlm 263-265).
Menurut Wellem, pendirian Wielenga dan Lambooy lunak.
Mereka tidak keberatan jika orang-orang Kristen meng am bil bagian dalam upacara-upacara adat tertentu demi kehidupan bermasyarakat. Wellem juga mengatakan bahwa W. van Dijk, Krijger, dan L.P. Luijendijk mempunyai pandangan yang tegas dan menolak unsurunsur adat yang berbau kafir.
Pendirian yang paling radikal adalah pendirian S.J.P. Goossens yang menyatakan bahwa seluruh adat itu adalah kafir.
Pendirian yang paling berpengaruh adalah pendirian tengah, melalui siswa-siswa Krijger (F.D. Wellem, hlm 231, 232). Hanya saja perkem bang an selanjutnya melampaui tujuan para peng anut pendirian te ngah itu. Sudah sejak tahun 1954 Sinode GKS mengesampingkan buku katekisasi karangan Van Dijk, karena tidak menyetujui per ingatan-peringatan terhadap marapu dan tuan tanah dan juga karena pendirian tajam terhadap Gereja Katolik Roma (F.D. Wellem, hlm 373, 374).
Th. Van den End, demikian juga B. Plaisier, telah membandingkan Zending di Sumba dengan Zending dari Gereformeerde Bond (GZB) dari Nederlands Hervormde Kerk di Tana Toraja. Plaisier heran mengapa corak GZB yang reformed itu hampir ti dak berakar dalam pola kehidupan dan kehi dupan rohani orang Toraja. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa para zendeling di sana dipengaruhi oleh pendekatan A.C. Kruyt dan N. Adriani di Poso, Sulawesi Tengah, yang termasuk dalam aliran ”etis” di Gereja Hervormd. Karena itu, mereka membiarkan para guru Injil Toraja itu membentuk kehidupan Kristen dengan gaya budaya mereka sendiri.24
Plaisier berpendapat, berlawanan dengan itu zendeling-zendeling di Sumba tidak begitu mengindahkan nasihat-nasihat guru Injil mereka. Untuk hal itu, Plaisier tidak menyebutkan alasannya, dan dalam tulisannya tentang pembandingan antara Toraja dan Sumba muncul begitu saja. Keterangan tentang perbedaan antara GZB dan Gereja Toraja masuk di akal, tetapi pembandingan dengan Sumba tidak. Di Sumba para zendeling mendengarkan pen dapat para guru Injil mereka.25 Di Sumba, gereja-gereja Kristen seperti GKS dan GGRI bercorak gereja pribumi.
Menurut Plaisier, justru gerejalah yang memelihara wa risan adat dan budaya Toraja sekalipun secara tidak sengaja.26 Upacaraupacara kematian di Toraja terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Masyarakat Toraja yang telah menjadi Kristen tetap meme gang dan melaksanakan upacara adat kematian itu, dan karena itu upacara-upacara penguburan menjadi berkembang.
Perkembangan di Sumba juga tidak berbeda, karena gereja memberi peluang untuk meneruskan adat-adat tertentu, sehingga di Sumba pun sekarang ini upacara pemakaman di adakan secara besarbesaran, baik di tengah orang yang belum percaya mau pun di tengah orang Kristen, setidaknya di GKS.
1.2. Memaksa atau Menumbuhkan
Apakah zending memaksa anggota jemaat yang baru masuk Kristen agar menerima sebuah pola hidup yang baru, atau betulkah zending memberi peluang agar mereka mengem bangkan budaya Kristen khas Sumba sebagaimana yang dikatakan di atas? Pertanyaan itu akan dijawab berdasarkan beberapa pokok tertentu. Pokok pem-belis-an belum termasuk dalam pembahasan bagian ini. Pokok pem-belis-an dibahas pada bagian 4.1.3 dan pokok siasat kristiani akan dibahas secara khusus dalam bagian 4.2.
Makan daging yang dipersembahkan kepada berhala
Zendeling pertama di Sumba Timur adalah J.J. van Alphen, yang disusul oleh W. Pos, J.F. Colenbrander dan S.J.P. Goossens, mereka semua bertempat tinggal di Melolo.
Pos menghadiri upacara-upacara orang-orang yang belum menjadi Kristen, pada kesempatan itu dia menyumbang kain dan menerima hewan. Di rumahnya dia meminta orang untuk menyembelih hewan tersebut. Orang-orang Kristen tidak memakan daging hewan kurban itu, meskipun demikian tetap terjadi saling pengertian yang baik dengan para tetangga.27
Colenbrander membedakan daging hewan yang dipersem bahkan dengan daging yang tidak dipersembahkan. Daging yang bukan dari hewan kurban dapat dimakan sebagai tanda persahabatan28.
Dalam rapat khusus para pendeta utusan (Bijzondere verga-dering van missionaire predikanten) pada tanggal 18 Mei 1934, para zendeling telah bersepakat mengenai boleh atau tidaknya makan daging hewan kurban. Rapat membahas bahan yang dimasukkan oleh Pdt. Goossens, berdasarkan catat an tertulis dari rekan-rekan kerja dan para guru Injil pribumi. Mereka semua mengajukan keberatan untuk meng hadiri pesta persembahan, tetapi lima dari tujuh belas guru Injil berpendapat bahwa makan di rumah sendiri boleh, bila daging itu diantar ke rumah dari rumah pesta. Laporan Goossens itu langsung pada pokok masalah dan membahas hal-hal tentang adat dan penafsiran ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karangan-karangan Pdt. Goossens yang ditulis kemudian sering bersifat menentang dan subyektif, tetapi laporan mengenai hal ini jelas dan obyektif.
D.K. Wielenga J.D.zn (artinya: anak dari J.D. Wielenga)29 menyebutnya ”satu artikel yang sangat baik”, dan menyetujui pan dangan Goossens yang mengutip perkataan seorang guru Injil: ”Dengan senang hati kami menghubungkan orang kafir dengan Tuhan, tetapi mereka hendak menghubungkan kami orang Kristen dengan marapu”.30
Sesudah rapat, hasil kesepakatan itu diedarkan ke semua lembaga yang berperan dalam masyarakat Kristen di Sumba. Surat itu ditandatangani oleh Krijger, Lambooy, dan Goossens.31
Para zendeling, dan hampir semua guru Injil, berpendapat bahwa daging yang berasal dari pesta, meskipun diantar ke rumah, tetap ada kaitannya dengan marapu. Hanya seorang guru saja yang membedakan antara dua macam daging an taran: mungkin saja daging itu berasal dari hewan yang di sembelih untuk di persembahkan sebagai makanan marapu, bila yang diantar itu da ging persembahan, jangan dimakan! Tetapi, mungkin saja daging itu memang telah didoakan tetapi dimaksudkan untuk menjadi makanan dalam peristiwa yang bersifat gotong royong, misalnya dalam membangun rumah atau mengerjakan ladang. Bila daging tersebut diantar ke rumah, boleh dimakan karena dimaksudkan untuk mempererat pergaulan di tengah masyarakat.
Yang paling tajam adalah penilaian dari ”Guru Kgg”; kemungkinan besar yang dimaksud oleh Goossens adalah Guru K. Tanahomba dari Kananggar. Guru tersebut berpendapat bahwa seorang penyembah berhala tetap mempunyai rasa takut terhadap dewa. Melalui persembahan itu mereka meng upayakan persekutuan dengan para dewa. Bagi orang-orang yang menyembah berhala, tiap per sekutuan menuntut persembahan, bahkan tiap doa. Dia berpendapat, daging yang diantar ke rumah bukan diperuntukkan bagi manusia, melainkan bagi marapu. Berbeda dengan yang tertulis di Alkitab dalam Korintus, di Sumba setiap bagian daging ada lah daging persembahan. Daging berbeda dengan jagung atau padi, yang ditanam untuk memperoleh makanan, dan orang Kristen menghargai Allah sebagai pemberinya, sedangkan menurut orang Sumba tiap hewan yang disembelih dimak sudkan untuk melayani marapu.
Sayang sekali, orang Kristen Sumba tidak mengubah pandangannya tentang daging. Alki tab meng ajarkan bahwa daging pun diberikan kepada manusia untuk menjadi makanan baginya (Kej 9:3). Sangat diragukan apa kah setiap orang Kristen ketika menyembelih hewan mempunyai perasaan yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh ”Guru Kgg”. Lebih tepat adalah alasan kedua yang disodorkan guru itu, yaitu orang Kristen yang menerima daging akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang menyembah berhala untuk masuk Kristen.
Pandangan P.J. Lambooy tentang daging yang diantar ke rumah, berbeda dengan pandangan Goossens. Dia mengatakan bahwa orang yang tinggal di rumah tidak akan menerima apa pun yang berkaitan dengan persembahan kepada marapu, kecuali jika dia mengutus wakilnya atau paling tidak mengirim pemberian. Tetapi, pandangan ini tidak kami temukan pada sumber lainnya. Dia juga mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan mengirim wakil atau pemberian. Jadi, jika dia menerima daging, jelas bahwa kiriman daging itu hanya bersifat sosial bukan religius.
1 Korintus 8-10 merupakan bagian Alkitab yang dijadikan landasan pandangan etis Goossens. Dia menafsirkan bahwa seluruh bagian ini ditujukan pada kelompok yang sama, yaitu mereka yang ”kuat” di Korintus. Tetapi, dia berpendapat bahwa kekuatan itu semu. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang di Sumba, khususnya orang Sabu, yang tidak keberatan untuk memakan apa yang dipersembahkan, sebenarnya hanya mencari untung: mereka senang karena dapat makan daging dengan cuma-cuma. Paulus menuduh orang ”kuat” di Korintus karena hal yang sama, yaitu mencari untung (1Kor 10:33). Kalau demikian halnya, menurut pendapat kami, alasan-alasan yang dikemukakan oleh ”Guru Kgg” dengan sendirinya tidak berlaku; bagi tiap orang di Sumba daging selalu merupakan daging persembahan.
Benar sekali pendapat Goossens bahwa pokok pikiran tentang memakan daging persembahan tidak boleh disetujui atas keyakinan bahwa berhala tidak ada. Karena dengan alasan itu, orang Kristen juga dapat ikut serta dalam upacara di kuil berhala, karena berhala tidak ada. Padahal semua orang Kristen dilarang untuk pergi ke sana.
Beberapa kesimpulan Goossens adalah: 1) daging persembahan yang diantar ke rumah tetap dan secara objektif berhubungan dengan marapu, meskipun tidak tiap orang akan merasakannya. Dengan memakan daging itu, secara subjektif, orang mulai ber hubungan dengan marapu; 2) dengan sadar memakan daging per sembahan merupakan larangan bagi tiap orang Kristen, berdasarkan ungkapanungkapan Rasul Paulus, terutama dalam 1 Korintus 8-10. Semua misionaris menandatangi surat edaran, yang dileng kapi dengan satu catatan lagi, yaitu bahwa daging yang di atasnya nama marapu tidak diserukan, tidak dapat disebut sebagai daging persembahan, kecuali jika hewan itu disembelih pada upacara penyembahan berhala (termasuk penguburan) sekalipun mungkin bentuk hati hewan itu tidak diteliti oleh imam marapu. Berarti, masukan Lambooy dihargai, yaitu bahwa daging dari hewan yang disembelih untuk kegiatan sosial, dapat diterima.
Masyarakat Sumba Timur, baik yang Kristen maupun yang tidak, kemudian mengembangkan kebiasaan untuk melakukan penyembelihan hewan dalam sebuah pesta secara terpisah dalam dua bagian. Dengan demikian, kata kerja ”menyembelih” diberi arti baru, karena sejak dahulu, pengertian menyembelih bagi orang Sumba sama dengan mempersembahkan, karena selalu ada sebagian yang diper untukkan bagi marapu yang selalu diiringi dengan doa. Tetapi, bagi orang Kristen, arti menyembelih menjadi: memotong hewan untuk dimakan dagingnya. Bila ada pesta yang undangannya dari orang Kristen dan non Kristen, maka anggota masyarakat Sumba memberi kesempatan kepada orang Kristen untuk menyembelih hewan secara terpisah dari penyembelihan hewan yang dipersembahkan bagi marapu.
Ada anggota Gereja GGRI yang mengajukan keberatan untuk memakan daging apa saja yang merupakan antaran dari rumah duka. Menurut kami, keberatan seperti itu tidak ada dasarnya, karena jika daging itu diantar dari rumah orang Kristen, apa salahnya, demikian juga bila diantar dari rumah orang yang bukan Kristen yang mengatur agar bagi orang Kristen ada penyembelihan hewan tersendiri.
Menurut N. Woly, di kalangan GKS, memakan daging persembahan tidak lagi dianggap sebagai dosa.32
Perbedaan sosial
Menghadapi perbedaan-perbedaan sosial tersebut, Zending pada umumnya mengikuti kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan sebelum Zending masuk ke Sumba, peme rintah telah melarang perbudakan. Dan intervensi yang dilakukan untuk menghentikan perdagangan budak belian di Sumba sangat kuat.
Akan tetapi, dengan penuh kesadaran Zending berusaha menjalin hubungan dengan generasi muda kaum bangsawan, agar dengan mendidik generasi muda kaum bangsawan itu, mereka dapat merangkul seluruh masyarakat. Di Sekolah Pen didikan Guru dan Sekolah Guru Injil, anak-anak bangsawan diterima dengan senang, karena bila seorang penginjil ber asal dari golongan rendah, wibawanya akan kurang dan ada kemungkinan Injil yang diwartakan akan mendapat peng hinaan dari orang Sumba.33
Wellem bercerita bahwa Sekretaris Umum GKS pernah dita nya oleh anggota majelis di pedalaman tentang status vikaris yang baru, yang hendak ditempatkan di jemaatnya, ”Anak siapa dia?” Sekretaris menjawab dengan tepat, ”Anak Tuhan”.34
Zending dan kemudian Gereja Sumba tidak memaksakan kehendak untuk meniadakan perbedaan-perbedaan sosial, dengan alasan bahwa di dalam Kristus seharusnya tiap orang setara dengan yang lain. Gereja lebih mendukung pertumbuhan secara spontan daripada memaksakan perubahan.35
S.J.P. Goossens mengungkapkan kritik yang tajam terhadap perbedaan golongan. Dia mempersalahkan orang-orang Kristen yang membeli hamba, meskipun hamba itu diakui sebagai anak piara, yang dengan maksud ”suci” dididik menjadi orang Kristen.36
Tempat pemukiman keluarga baru
Apakah suami istri yang baru menikah diharuskan tinggal di tem pat orangtua, atau mereka dapat bebas memilih? Saat ini, pi lihan bebas itu sesuai dengan keinginan pemerintah, yang meng hen daki agar para penduduk mendiami seluruh pulau seca ra merata. Upaya itu dilakukan, antara lain melalui proyek resettlement. Pertanyaannya adalah apakah sebelumnya Zending juga mendorong hal yang sama? Rupanya tidak, dan juga tidak mengutamakan pilihan bebas bagi keluarga muda.
Hal yang lain adalah bahwa Zending berusaha mendekati seluruh penduduk melalui pendidikan, dan hendak memberikan harapan dan wawasan yang luas untuk masa depan, khususnya bagi mereka yang berkesempatan mengikuti pendidikan lanjutan di luar tempat tinggal mereka. Zending juga menawari para pemuda untuk tinggal di asrama. Di Pusat Latihan Petani Kristen (PLPK), suatu proyek modern yang terletak di Lewa, diupayakan untuk menciptakan pandangan baru mengenai keluarga dan masyarakat, disertai dengan metode pertanian yang baru. Tetapi, tidak pernah ada pemaksaan, dan pandangan baru itu tidak bertujuan untuk merusak atau memutus hubungan dengan keluarga.37
Zending juga tidak pernah berpikir untuk mendirikan per kampungan Kristen. Malah sebaliknya, sudah sejak lama di Indo nesia modern ini jaringan keluarga diperluas sampai ke kota ka bupaten, Waingapu dan Waikabubak, sampai ibu kota provinsi di Kupang, bahkan sampai di Jakarta. Bila ada kaum muda yang mengikuti kuliah di tempat-tempat tersebut, sedapat mungkin akan tinggal di rumah keluarga.
Individualisme
Zending yang kebarat-baratan sering cenderung untuk menentang sistem kolektivisme yang ditemukan di tengah masyarakat suku. Apakah hal itu juga terjadi di Sumba? Mungkin ada kecenderungan emosional dan bersifat pribadi semacam itu pada para zendeling, demikian juga pada para ahli pertanian sering menilai kolektivisme sebagai peng hambat perkembangan.38 Namun, karya pembangunan makin dikaitkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di masyarakat setempat, dan tidak ada maksud untuk dengan paksa memutuskan hubungan dengan itu.39 Seorang petani yang ber tindak sangat individualistis, pada saatnya akan mengalami ke gagalan dibandingkan dengan para petani lainnya.
Satu bukti yang lain bahwa gereja tidak tertarik pada individualisme adalah munculnya kebiasaan yang disebut ”perbaikan nikah”. Gereja dengan benar menyatakan bahwa hidup bersama di luar nikah merupakan penentangan terhadap makna keluarga. Orang-orang muda dinyatakan bersalah karena melanggar Hukum Kelima, sedangkan para orangtua juga dipersalahkan karena mereka tidak berhasil membina anak mereka dengan baik dan membiarkan mereka melakukan ”kawin duduk”. Individualisme tidak akan bertumbuh di lingkungan gereja yang di dalamnya sanksi bagi pelanggar hukum biasa diterapkan.
Jika dibandingkan dengan para zendeling lainnya, Lambooy lebih menekankan perhatiannya terhadap hal ini. Bersama dengan jemaat dia melakukan pembahasan untuk mempertimbangkan unsur-unsur adat mana yang dapat dipertahankan dan mana yang harus ditiadakan. Jelas baginya bahwa tidak semua unsur adat itu dapat disebut pekerjaan Iblis. Mempertimbangkan hal itu, yang hendak dipertahankan, antara lain adalah belis, karena hal itu merupakan bukti sahnya suatu perkawinan. Demikian pula unsur denda dan penyesalan hendak dipertahankan, tetapi sanksi itu dialihkan ke siasat gerejawi.
Alangkah baiknya kalau pendekatan kepada manusia dilakukan seutuhnya, tidak secara individual. Kehidupan masyarakat juga memengaruhi gereja, meskipun bukan hakikat gereja atau ajar annya, tetapi tampak dalam penyusunan hukum gereja, tata cara ibadat dan gaya bangunan gereja. Wellem mengatakan bahwa Lambooy telah memikirkan mengenai hal-hal yang kemudian hari disebut sebagai konteks tualisasi40.
1.3. Belis Sebagai Batu Sandungan
Tentu saja belis merupakan unsur yang menjadi paling pokok pembicaraan dalam proses kristenisasi di Sumba Timur. Pada mulanya para zendeling secara spontan menentang belis, sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah zending lain. Van den End menunjukkan ungkapanungkapan yang disampaikan oleh Wielenga (1911) yang menyebutnya ”harga pembelian”, Colenbrander (1924/1925) yang mengatakan bahwa ”perempuan dianggap barang dagangan”, dan Luijendijk (1957) berkata-kata tentang ”beban yang terlalu berat”. Residen A.J.L. Couvreur (1921-1924) mengatakan, pem-belis-an meru pakan salah satu penyebab menurunnya jumlah pen duduk di Sumba.41
Khususnya dalam laporan-laporan Goossens (1935/1936) kami temukan keberatan-keberatan yang kuat untuk menentang belis42. Tetapi, meskipun tidak ada seorang pun yang setajam dia, dalam banyak hal para zendeling lainnya berpandangan yang searah dengannya.43
Akan tetapi, pada awalnya di antara para zendeling itu juga telah memahami bahwa pada kenyataannya penyerahan perem puan sesuai dengan adat, telah memberi kekuatan pada kehidupan bermasyarakat.
Pada awalnya Lambooy senang mendengar bahwa para penduduk di Karita (Sumba Tengah) telah memutuskan untuk tidak lagi menuntut belis. Tetapi, Onvlee yang pada waktu itu sudah lebih lama tinggal di Sumba, menasihati agar berhati-hati, berdasarkan pengalamannya di tempat lain. Onvlee berpendapat bahwa perkawinan tetap harus diatur sebagai urusan keluarga, karena seluruh masyarakat masih terorganisasi sedemikian kuat menurut keluarga-keluarga.44
Justru Lambooy yang mempertahankan belis karena dalam pandangan masyarakat, di situlah letak ke kuatan hukum perkawin an.45 Dia tidak setuju dengan pendapat Goossens yang menurutnya tidak meneliti masalah belis dengan benar dan mendalam.
Demikian juga Pos, satu di antara orang pertama yang bekerja di Sumba, menganggap belis sebagai unsur kekuatan perkawinan.46
Wielenga, T. van Dijk dan Luijendijk berpendapat, tidak benar jika perkawinan di Sumba disebut sebagai perkawinan pembelian. Yang ditemukan adalah suatu perjanjian antar keluarga, dan merupakan mata rantai di dalam sebuah sistem ekonomi yang menyeluruh. Kadang-kadang pemberian balasan lebih besar dari pada belis.47
Gereja Katolik Roma di Sumba Barat juga menggumuli masalah yang sama. Terdengar keluhan bahwa perkawinan dilakukan semata-mata karena para orangtua mementingkan diri sendiri. Jika anak mereka menikah, mereka akan dapat membayar lunas utang dari perkawinan yang telah diadakan lebih dahulu.48 Seorang suster berkata bahwa selama gadis-gadis berada di asrama susteran, masa muda mereka diper panjang karena perkawinan mereka tertunda.
Dengan demi kian, mereka luput dari perkawinan yang dipaksakan oleh orangtua.49
Benarkah perempuan dibeli?
Di Sabu ada kata yang digunakan untuk mengungkapkan harga pembelian perempuan. Meskipun demikian, perempuan dalam budaya Sabu, apalagi seorang ibu, mendapat peng hargaan yang ting gi.
Suku kata ’li’, yang banyak ditemukan dalam kata-kata di Indonesia Timur, menurut beberapa orang tertentu pada mulanya berarti ”pertukaran”.50 Tentu saja ”harga kawin” lebih bersifat pertukaran bukan pembelian.51
Menurut Rodney Needham, kata vali dalam bahasa Mamboru, terjemahan yang lebih tepat adalah ”nilai” (value) bukan ”harga”, untuk membeli sesuatu.52
Umbu Hina Kapita menerangkan bahwa dalam bahasa Kambera, kata wili berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia ”beli”, demikian juga kata belis, yang sering ditemukan dalam bahasa di Indonesia Timur. Tetapi, menurut Kapita, baik wili mau pun belis artinya adalah nilai, bukan harga53.
Dalam sebuah ceramah yang berjudul Cultuur alsantwoord (Budaya selaku jawaban), L. Onvlee mendalami masa lah etnosen tris medalam proses penerjemahan. Kadang-kadang tidak ada ke mungkinan lain selain menerjemahkan dengan satu kata yang dapat dipastikan bahwa oleh pembacanya akan diberi pan dangan dan pemahaman sendiri yang tidak sesuai dengan maksud awal nya. Dia mengatakan, ”Saya ingat bahwa saya pernah ber usaha menjelaskan kepada seorang rekan kerja apa arti kata wili dan belis, yang secara etimologi mempunyai arti sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia ’beli’. Dan saya jelaskan juga peran belis itu dalam masyarakat Sumba.” Demikian juga kita memang sering harus menerjemahkan dengan kata kerja bahasa Belanda kopen, te tapi artinya berbeda dengan kata kopen dalam pengertian yang dipahami oleh masyarakat Belanda, dan tidak boleh dikaitkan dengan pandangan yang berlaku dalam budaya Belanda, di samping itu terjemahan tersebut tidak boleh menimbulkan kesimpulan yang keliru. Hal itu memunculkan tanggapan, ”Kalau begitu, mengapa mereka menyebutnya kopen? Memang, budaya asing harus didekati secara non-etnosentris”.54
Menurut pengalaman kami, dalam bahasa sehari-hari dengan jelas memang dikatakan ”membeli”. Orang sering menga takan: ”Orang itu belum membayar lunas belis”, ”Perempuan itu telah dibelis-kan”, ”Dia harus membayar denda” (belis yang dinaikkan, karena sudah mempunyai anak).
Adakalanya, orang berkomentar tentang seorang perempuan, ”Dia terlalu mahal, tidak dapat dinikahi”. Karena baik di Sumba maupun di Sabu memang berlaku kebiasaan bahwa belis untuk seorang perempuan tidak boleh kurang dari belis yang dahulu diba yarkan untuk ibunya.55 Tetapi, dapat juga terjadi bahwa pada akhirnya keluarga menyetujui suatu cara perkawinan yang di dalamnya tuntutan belis tidak terlalu besar, dengan alasan bahwa tidak ada lagi yang akan datang untuk mengambil putri mereka dengan belis yang wajar.
Hanya, perlu dipertimbangkan apakah berdasarkan ungkapanungkapan seperti yang tertera di atas, orang Sumba dapat dini lai sebagai masyarakat yang tidak menghargai perempuan. Ungkapanungkapan yang sifatnya diskriminatif itu terdengar di mana-mana, namun tidak perlu dianggap sebagai pegangan.
2. Gereja-gereja Reformasi ei Samba (1936-1984)
Di Sumba Timur terdapat dua gereja kecil yang sama-sama berasal dari suatu pertikaian gereja pada tahun 1936-1938, yaitu Gerejagereja Reformasi dan Gereja-gereja Bebas. Mereka terpisah dari gereja yang besar, yang kemudian disebut Gereja Kristen Sumba. Alasan mengapa sampai terdapat dua gereja dan bukan satu di samping GKS, adalah karena adanya perpecahan lain pada tahun 1951-1953.
Menurut Van den End, ”Alasan perpecahan tahun 1938 adalah karena dia (S.J.P. Goossens) tidak menyetujui bahwa rekan-rekan kerja menerima unsur-unsur adat, seperti pem-belis-an, di jemaat Kristen.”56 Secara formal pem-belis-an bukanlah pokok masalah yang terjadi pada tahun 1936 dan 1952. Tetapi, pem-belis-an merupakan unsur adat yang paling mencolok dan yang selalu berpengaruh. Pemimpinpemimpin di Gereja-gereja Bebas mengatakan bahwa persatuan dengan GGRI akan sulit terlaksana, karena kalau demikian, anggota jemaat akan kembali ke pem-belis-an.
Tahun 1936
Pada tahun tigapuluhan banyak zendeling asal Belanda yang ber tugas di Sumba, masing-masing bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Zendeling untuk Sumba Timur adalah Pdt. S.J.P. Goossens, dan pertikaian tahun 1936-1938 terjadi di wilayah itu. Karena itu, justru di Sumba Timur terbentuk sebuah gereja tersendiri.
Pdt. Goossens belum lama bekerja di Sumba, tetapi telah banyak suara yang mengatakan bahwa dia maupun Penginjil K. Tanahomba, merusak budaya Sumba.57 Penginjil tersebut menolak membayar belis yang dituntut oleh keluarga istrinya yaitu keluarga raja di Kananggar.
Seorang pendukung Goossens lainnya adalah Penginjil L.
Kondamara, dia dan banyak orang Kristen lainnya tetap membayar belis. Selain itu mereka juga mengutamakan hal pemilihan jodoh yang hendaknya didasarkan pada cinta kasih, bukan berdasarkan kemauan keluarga.58 Pada perpecahan yang kedua, Kondamara berubah menjadi penentang Goossens dan Tanahomba.
Menurut beberapa orang, penyebab pertikaian tahun 30-an adalah bahwa Goossens bertindak sendiri, dan memu tuskan segala sesuatu sebelum melakukan pembahasan dengan matang.59 Orang lain berkesimpulan bahwa rekan-rekan kerja maupun gereja-gereja di Belanda berprasangka terhadap Pdt. Goossens karena mereka tidak setuju dengan pandangannya yang prinsipiel itu.60
Tentang pokok-pokok perpecahan pada tahun 1936-1938:
Gereja Melolo mempersoalkan mengenai pokok siasat terhadap orang Kristen yang telah menerima daging yang diper sembahkan kepada berhala pada pesta berhala61.
Masalah Umbu Katu di Baing, seorang muda lulusan SPG Kristen di Makassar, hendak diangkat sebagai guru di suatu sekolah zending, hanya saja dia belum dibaptis, apalagi sekembalinya ke daerah asalnya, dia belum membuktikan dengan buah hidupnya bahwa dirinya telah menjadi seorang Kristen.
Mengenai kemandirian institusi gereja Kananggar, menurut pandangan gereja-gereja di Sumba Timur, maupun zendeling Goossens, jemaat itu siap mandiri, tinggal menunggu hasil pene litian oleh sidang pekerja Zending, sesuai dengan peratur an yang ada. Karena pene litian tersebut terus ditunda maka akhirnya jemaat Kananggar berdiri sendiri tanpa persetujuan sidang pekerja zending.
Di mana letak masalahnya?
Ad 1. Kasus ini, mengenai penanganan siasat, memang merupakan hal yang terpenting. Dan barangkali merupakan pokok yang terpenting pada pembahasan di sinode Sneek-Utrecht (1939-1943), untuk menilai tindakan gereja pengutus (Appingedam) dalam melaksanakan siasat terhadap Pdt. S.J.P. Goossens. Sinode itu telah menerima laporan dari panitia W.H. den Houting yang berkesimpulan bahwa skorsing maupun pemberhentian terhadap Pdt. Goossens adalah salah. Tetapi, sinode tidak menyetujui la por an itu, sebab telah masuk satu laporan yang lain, yaitu dari H. Bergema, yang menyebabkan pandangan umum di Sinode berbalik arah.62 Laporan Bergema itu secara rinci membahas ke bijakan menge nai siasat di Sumba. Bergema khawatir terhadap adanya begitu banyak peraturan terhadap agama Kristen formal. Karena kalau demikian, pertentangan dengan Injil tidak akan ada habisnya. Menyangkut peraturan-peraturan, tidak setiap peraturan bertujuan menjadi hukum yang tetap dan terus-menerus berlaku. Sebagian dari peraturan tidak lebih dari satu langkah menuju ke pemenuhan tuntutan seluruhnya, dan peraturan itu sewaktu-waktu dapat berubah. Tujuan ak hir nya adalah pengkristenan masyarakat.
Pdt. B.N. Radjah, di Melolo, seorang pendeta dari GGRI, telah menyusun tulisan tentang sejarah GGRI Sumba Timur. Pan dangannya mengenai masalah Melolo cukup jelas. Di Melolo ada seorang guru ”yang tidak setuju dengan keputusan majelis gereja tentang daging atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Beliau memakan saja daging persembahan itu di tengah pesta orang-orang yang menyembah berhala”.63
Ad 2. Tentang permasalahan Calon Guru Umbu Katu, terjadi eskalasi yang tidak diinginkan. Pdt. Goossens tidak bersalah. Dia berencana mengunjungi jemaat asal orang muda itu dan membawa surat panggilan dari kepala dinas pendidikan yang isinya adalah bahwa si guru harus datang ke tempat kerjanya untuk mulai bertugas. Dalam kunjungan itu Goossens menemukan kenyataan bahwa orang muda itu, selama di kampung halamannya, tidak pernah ke ge reja. Karena itu, dia menunda keberangkatan si pemuda untuk mulai melaksanakan tugas mengajarnya. Goossens menyuruh pemuda itu memperbaiki kehidupannya lebih dahulu.64 Akibatnya, kepala dinas pendidikan tersinggung dan berpendapat bahwa Goossens ikut campur dalam urusannya. Tetapi, seandainya keduanya mau berusaha memahami alasan masing-masing, masa lah itu tidak berkembang. Zendeling itu kecewa terhadap tingkah laku pemuda itu setelah dia kembali ke desanya, sedang pejabat pendidikan itu ingin agar si pemuda segera bertugas setelah studi nya selesai, sesuai dengan tujuan studinya, dan juga berharap bahwa dia akan ikut katekisasi dan kebaktian di tempat kerjanya.65
Menurut B.N. Radjah, keberatan Goossens sah adanya, ka re na dalam peraturan zending ”orang yang bukan Kristen tidak diizinkan mengajar atau menjadi guru di sekolah Kristen”. Per aturan yang sama berlaku bagi guru-guru lain yang mengikuti pendidikan di Pulau Sumba.66
Ad 3. Dalam hal kemandirian Kananggar, sidang pekerja Zending melakukan kekeliruan dengan tidak menghiraukan permohonan Kananggar tersebut. Hal ini patut disesalkan dan sangat tidak bersifat pastoral terhadap orang Kristen di Sumba Timur. Rapat itu memutuskan demikian karena tidak senang pada Pdt. Goossens.67 Dapat dipahami bahwa Kananggar dimandirikan tanpa persetujuan sidang zending itu.68
B.N. Radjah bertanya mengapa pokok kemandirian Kanang gar tidak dipercayakan kepada gereja-gereja di Sumba Timur, yang pada waktu itu telah berdiri sendiri? Dan mengapa para zen deling tidak memikirkan bahwa gereja-gereja yang telah berdiri sendiri dapat membentuk sebuah klasis? ”Atau mungkin, karena pada waktu itu Indonesia dijajah Belanda, sehingga kuasa dan kedaulatan gereja ditindas?”69
Mengenai siasat, pandangan Goossens memang jauh lebih keras daripada pandangan rekan-rekannya. Pokok asasi ini seharusnya pada waktu itu dibahas bersama sampai tuntas. Rekannya, Pdt. W. van Dijk di Sumba Barat pernah menu turkan tentang poligami, ”Apakah hal itu tidak sepatutnya kita serahkan kepada kuasa Roh Kudus, asalkan kita membimbing mereka dengan setia?” Goossens menanggapi, ”Dengan pasti Kitab Suci menyatakan apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang tetap berkubang dalam dosa yang ngeri itu. Namun, Pdt. Van Dijk merasa lebih tahu, dan dia merasa bahwa kamilah yang menghabiskan mereka dengan ’rotan’ siasat yang menyembuhkan.”70
Pada akhirnya Goossens dipecat oleh gereja pengutus, gereja di Appingedam, pada tahun 1939. Kemudian beliau berangkat ke Belanda bersama beberapa orang kepercayaannya, untuk membela diri di Sinode Umum. Tetapi, permohonannya agar keputusan pemecatan ditinjau ulang ditolak. Gereja-gereja muda di Sumba Timur mendukung zendeling mereka dan membentuk sebuah perserikatan gerejawi tersendiri. Pada Sinode Umum yang pertama sesudah Pembebasan Gereja di Belan da (1944), yaitu pada tahun 1946, Goossens sekali lagi memohon peninjauan ulang terhadap keputusan mengenai pemecatannya. Dan sinode itu memulihkan ja batannya. Kemudian Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) juga
2. Gereja-gereja Reformasi ei Samba (1936-1984) menjalin hubungan dengan Gereja-gereja Gere for meerd di Sumba Timur, yaitu gereja-gereja yang menjadi pengikut Pdt. Goossens.Pada tahun 1939, Pdt. Lambooy mengadakan konferensi ten tang adat, khususnya bagi para majelis gereja di jemaat-jemaat orang Sabu di pesisir pantai di Sumba Timur, bersama peng injil-penginjil yang bertugas di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Penilaian adat mulai dilakukan secara teratur. Hanya saja, hasilnya tidak akan kami bahas dalam penelitian kami ini karena yang dibahas adalah tentang adat Sabu, apalagi adat perkawinan, hanya disinggung sedikit71.
Tahun 1952
Pada perpecahan yang kedua, tahun 1951-1953, sekali lagi Goossens berbeda pendapat dengan gereja pengutus, dalam hal ini gereja di Zwolle. Dan sekali lagi pelaksanaan siasat menjadi pokoknya. Kali ini Guru Injil L. Kondamara diberhentikan sementara, karena dia merupakan ketua dari lembaga persekolahan Zending. Bersama dengan B.N. Radjah, yang menjabat sebagai sekretaris, mereka mengadukan Goossens kepada gereja pengutus. Bersama dengan utusan dari Zwolle lainnya mereka juga mengadakan kebaktian tersendiri, berlawanan dengan kebaktian yang dipimpin oleh ma jelis lokal dan zendeling. Pendamaian hampir saja tercapai, te tapi ketika penginjil diminta untuk menarik pengaduannya, dia menolak, sehingga dia diberhentikan. Pada waktu itu Pdt. Goossens sedang berada di Belanda.
Permasalahannya ialah bahwa menurut para zendeling, badan sekolah berada di bawah pengawasan mereka, termasuk penetapan gaji. Sedang menurut badan persekolahan dan gereja pengutus, tidak demikian halnya. Jadi, perkara ini adalah permasalahan kompetensi.72
Gereja-gereja yang menerima Pdt S.J.P. Goossens dan kemu dian anaknya, Pdt. P.P. Goossens, menetapkan dan mengesahkan nama yang telah diberikan sesudah tahun 1938, yaitu Gereja-gereja Bebas.
Sesudah tahun 1952
Di Gereja Reformasi, tuntutan dalam pem-belis-an secara resmi telah dilarang.73 Begitu juga di Gereja Kristen Sumba.74
Secara jelas dan terbuka Gereja Reformasi telah menentang kebiasaan yang di dalamnya orangtua telah membayar sebagian belis kepada orangtua yang baru saja dikaruniai seorang anak perempuan (wiri bara).75 Menjodohkan anak sejak kecil sudah jarang terjadi di kalangan warga gereja.76
Selain kedua pokok yang telah disebutkan, tidak ada bukti tertulis dalam keputusan-keputusan GGRI. Tetapi, ada banyak larangan lain yang diberikan secara lisan:77
- bahwa babi yang telah diberikan oleh keluarga perem puan, harus dibalas dengan kerbau, untuk menghindari malapetaka. Jadi, agaknya hal ini untuk menentang ke biasaan seperti yang berlaku di Sabu yang menyebutkan bahwa kerbau itu untuk dewa, yaitu kerbau yang diterima oleh saudara lakilaki dari ibu;
- bahwa wunang (juru bicara) harus berteriak dengan keras agar marapu dapat mendengarnya;
- bahwa utusan pihak perempuan datang meninjau lebih dahulu, untuk menilai kekayaan pihak laki-laki, sehingga dapat memperkirakan besarnya tuntutan yang akan diminta;
- bahwa diadakan pesta mewah, yang memboroskan modal;
- bahwa sebagian belis dapat dikatakan ”denda”;
- bahwa kedua kekasih telah hidup serumah agar cepat mendapat anak dan penyelesaian adat ditunda dahulu.
Kenyataan terakhir dikemukakan dalam rapat oleh seorang Sumba asal Sabu, Pdt. B.N. Radjah, dan pandangannya dise tujui dengan diam-diam oleh yang lainnya. Memang, orang Kristen di Sumba menentang kebiasaan-kebiasaan yang langsung berhubungan dengan agama penyembah berhala, tetapi mereka tidak menentang dengan kuat penyalahgunaan belis. Dan secara tidak resmi penuntutan juga dibiarkan terjadi. Hal ini dilakukan antara lain oleh Pdt. Kondamara dan keluarganya.
Dalam pandangan pemerintah, orang Kristen cukup menikah secara gerejawi sehingga pengurusan adat tidak lagi diperlukan. Hanya penganut marapu yang terikat pada pem-belis-an. Bagi war ga negara Indonesia, perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi, pemerintah akan melindungi perkawinan orang Kristen yang diteguhkan di gereja meskipun orangtuanya tidak setuju.
Dalam hal seperti ini, gereja harus berani tampil untuk menentang orangtua dan sanak-saudara bila mereka menyalahgunakan adat.
Gereja-gereja Bebas melihat bahwa dalam praktik terdapat banyak penyelewengan, karena itu dalam tata gerejanya dicantumkan pasal yang menyangkut perkawinan, yang di dalamnya memuat larangan segala pemberian secara adat.78
Dikatakan bahwa semula di kalangan Gereja-gereja Bebas, belis, yang berupa seekor kuda disetujui,79 tetapi kemu dian hanya penge sahan dari pemerintah yang dianggap ber laku untuk mene guhkan perkawinan. Larangan pem-belis-an mengakibatkan terja di nya pemisahan dengan Jemaat Tana Righu (Sumba Barat) pada tahun 1983.80 Tidak hanya di sana, tetapi juga di tempat lain, ang gota gereja atau jemaat memisahkan diri dan bergabung dengan GKS atau GGRI dengan alasan yang sama.
Demikian juga di GGRI, perkawinan yang disahkan oleh pemerintah (pencatatan sipil, BS) dianggap penting. Meskipun pemerintah berkehendak bahwa gereja lebih dahulu meneguhkan perkawinan secara gerejawi, baru pencatatan sipil, ternyata dalam praktiknya pencatatan sipil dilakukan lebih dahulu. Apalagi secara khusus gereja menganjurkan agar melakukan nikah di pencatatan sipil jika kedua calon mempelai belum mengaku percaya atau menjadi anggota sidi sehingga untuk sementara belum dapat melakukan perkawinan secara gerejawi.81
Di kalangan GGRI sering diusahakan untuk menangani pem-belis-an secara bernuansa, tetapi usul-usul untuk mengaturnya dengan baik selalu gagal. Pada tahun 1984 Majelis Gereja di Lai Handangu mengeluarkan satu aturan yang sebenarnya dapat menyese laikan masalah, yaitu keputusan dari Majelis Gereja Lai Handangu, tanggal 24 Mei 1984, yang diterima oleh Klasis Pantai pada tanggal 29 mei 1984. U. Ngg. Rawambaku mempertahankan usulan itu dengan tujuan untuk membatasi belis sekaligus meng arahkannya ke tujuan yang baik. Di bawah ini tergambar latar belakang diskusi majelis tersebut.
Pokok adat perkawinan dibahas atas usul Yakerrsum, satu yayasan kesejahteraan di GGRI. Menurutnya, penyederhanaan adat perkawinan diperlukan demi pembangunan masyarakat. Di cari cara untuk menghemat materi dan menghemat waktu. Maje lis Gereja maupun Klasis sependapat.
? IV Penilaian Etis Selain itu, rapat-rapat gerejawi juga menerima dan menyetujui kritik yang dikemukakan oleh Yakerrsum yang menyangkut penyatuan kabihu, sebagai inti adat Sumba, dengan melangkahi kepentingan keluarga baru. Tetapi, pandangan umum itu baru tercapai sesudah diskusi yang pan jang dan hebat. Sebab, pada mulanya orang-orang Kristen yang berasal dari Sumba berpendapat bahwa belis bukan untuk kepentingan rumah tangga baru, melainkan untuk keluarga. Menurut adat, penuntutan belis diperbolehkan, tetapi penuntutan balasan tidak. Apalagi, menurut sebagian pembicara di rapat majelis tersebut, tujuan belis adalah pengganti perempuan. Sebab, sesuai dengan adat, perempuan tidak dapat membawa unsurunsur belis yang diterima untuknya ke dalam rumah tangganya.
Pada mulanya Majelis menentang pendapat Yakerrsum bahwa belis sering dilihat sebagai ganti rugi pendidikan dan pemeliharaan. Menurut Majelis, Yakerrsum juga keliru dalam asumsinya bahwa pasangan baru tinggal bersama dengan orangtua, karena merekalah yang membiayai pesta perkawinan. Menurut Majelis, alasan yang sebenarnya adalah kebutuhan pemeliharaan terhadap orangtua atau juga karena keluarga baru itu belum mempunyai rumah.
Akan tetapi, seluruh peserta sepakat bahwa keluarga-keluarga sering mengeluarkan uang lebih dari yang tersedia demi menjaga nama keluarga. Bahkan sering juga kedua belah pihak dirugikan. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan menyangkut pem-belis-an sering disertai dusta dan penipuan. Misalnya, pihak pengambil perempuan dengan mudah berjanji untuk membayar dengan jumlah tertentu kemudian hari, tetapi pada kenyataannya hanya bohong belaka.
Umbu Nggandi mengajukan usul-usul konkret hingga tercapailah kesesuaian pendapat. Menyangkut waktu, batas nya adalah tiga hari: satu hari untuk peminangan/masuk minta/menghadap, dan pada waktu itu seharusnya pihak perem puan telah mengundang keluarganya. Kemudian, satu hari untuk musyawarah keluarga. Dan terakhir adalah hari perkawinan, diawali dengan perkawinan secara gerejawi dan kemudian penyerahan pemberian di rumah perempuan.
Menyangkut pemberian, disarankan pada hari meng hadap sedapat mungkin keluarga pihak laki-laki memba wa dua ekor kuda; yang satu dimaksudkan sebagai ”kuda ketok pintu” dan yang satu lagi dimaksudkan untuk kepentingan intern pihak perempuan, ”kuda musyawarah”. Di samping itu, juga diserahkan dua buah mamuli.
Pihak perempuan menyembelih seekor babi dan memberikan sehelai kain dan sehelai sarung.
Umbu Nggandi mengatakan, hendaknya keluarga pihak perempuan tidak mengadakan pertemuan keluarga yang bersifat luas untuk musyawarah intern. Karena justru hal itu akan menyebabkan kesulitan; anggota keluarga jauh yang turut diundang akan ikut menuntut belis. Untuk menghindari kesulitan itu, hendaknya orangtua laki-laki pada hari menghadap, langsung mengatakan bahwa akan membawa empat ekor kuda, supaya keluarga perempuan tidak datang dengan banyak kain dengan tujuan agar memperoleh banyak hewan. Hendaknya keluarga laki-laki mengungkapkan dengan terus terang bahwa anaknya adalah anak Tuhan, bukan anak keluarga.
Apabila pada hari kedua yang ditentukan, yaitu hari musyawa rah, kedua keluarga bertemu di rumah laki-laki maka tanggal perkawinan langsung ditentukan. Pada hari itu seekor babi disembelih dan dibalas dengan apa saja yang dibawa keluarga perempuan.
Pada hari perkawinan, yakni hari ketiga, yang utama dan dilakukan pertama-tama adalah perkawinan gerejawi, sesudah itu baru dilaksanakan beberapa upacara lainnya. Pihak laki-laki ber terima kasih dan membuktikan itu dengan menyerahkan empat ekor kuda bersama dengan ma muli, yang hanya diberikan kepada orangtua perempuan, bukan keluarga lainnya. Inilah yang sering disebut ”pokok belis”. Sesudah itu diucapkan kata perpisahan dari pihak perempuan bersama penyerahan balasan. Mudah-mudahan tidak banyak pemberian yang diserahkan, karena dengan dilaksanakannya perkawinan gerejawi, sebenarnya semua sudah selesai. Seandainya pihak laki-laki memberikan lebih dari yang disebutkan, pemberian itu boleh diberikan kepada kedua mempelai, dan tidak perlu dibalas.
Pembahasan tentang GGRI-NTT diakhiri pada tahun 1984, yaitu tahun keluarnya keputusan Lai Handangu dan Klasis Pantai. Pada seminar tahun 2003, utusan-utusan dari GGRI secara garis besar mendukung anjuran-anjuran Lai Handangu.
3. Kontekstualisasi dan Kristenisasi
Dalam rangka penelitian ini mau tidak mau kami harus memikirkan dua wawasan dasar, yaitu kontekstualisasi dan kris tenisasi. ”Kontekstualisasi” berarti: upaya dalam pekabar an Injil dan pertumbuhan gereja dengan memperhitungkan konteks. ”Kristenisasi” yang merupakan tahap berikutnya adalah upaya gereja Kristen yang sudah bertumbuh itu untuk memengaruhi konteks. Tentu kita perlu juga mendefinisi istilah konteks. ”Konteks” itu adalah tiap lingkungan yang di dalamnya Injil dikabarkan dan gereja ber tumbuh, yaitu ling kungan konkret yang ditentukan oleh tempat, waktu, dan keadaan.
Ungkapan ”kontekstualisasi” agak modern, sedangkan kata ”kristenisasi” (pengkristenan) sudah lama dipakai. Ke dua ungkapan itu pada saat ini lazim digunakan di bidang misiologi. Munculnya ”kontekstualisasi” berhubungan dengan munculnya ilmu komunikasi modern. Pada tahun 1972, Shoki Coe meluncurkan kata itu, menggantikan ”indigenisasi”, atau ”pribumisasi”. ”So in using the word ’contextualization’, we try to convey all that is implied in the familiar term indigenization, yet seek to press beyond for a more dynamic concept which is open to change and which is also future-oriented.”82
Kontekstualisasi adalah kata inti dalam laporan Ministry in context dari Theological Education Fund (satu badan Interna tional Missionary Council, IMC) pada tahun 1972. Shoki Coe adalah direktur badan tersebut. Laporannya mengungkapkan ketidak puasan terhadap pendidikan-pendidikan tradisional dan mendo rong untuk lebih mendukung program-program yang kontekstual83.
Bagi kami, ungkapan ”kontekstualisasi” perlu disertai dengan ungkapan ”kristenisasi”. Kedua ungkapan tersebut menunjukkan secara bersama sebuah proses dalam dua tahap yang berbeda.
Dalam pandangan kami, kontekstualisasi menunjukkan ada nya kebutuhan dalam pemberitaan Injil dan pembangunan gereja agar menghiraukan masyarakat dan lingkungan, yaitu konteks. Shoki Coe menyebutnya sebagai ”contextuality”, yang harus diikuti dengan ”contextualization”, yaitu gerakan dan aktivitas yang meng ikutinya.84
Dalam pandangan kami, kristenisasi menunjukkan bahwa jemaat Kristen seharusnya memengaruhi masyarakat di sekitarnya. Jadi, konteks yang dikristenkan.
Dengan menggunakan kedua ungkapan tersebut maka arah kedua kegiatan itu jelas: konteks yang kultural itu mengarah ke jemaat Kristen (kontekstualisasi) dan pengaruh Kristen mengarah ke masyarakat (pengkristenan).
Sayang, para misiolog pada masa kini membatasi diri pada satu ungkapan saja, yaitu kontekstualisasi. Saat membi carakan hal itu, mereka membahas seluruh sejarah teologi, mulai dari Bapak-bapak gereja pada abad-abad yang pertama, dengan menekankan bahwa teologi sejak semula turut di bentuk oleh konteks.85 Sejak tahun 1961 di lingkungan World Council of Churches (WCC) dikenal pandangan bahwa agama-agama yang bukan Kristen juga bersifat menye lamatkan dan menyatakan keselamatan. Apalagi secara khusus yang diperhatikan adalah konteks politik, karena WCC terpengaruh oleh teologi pembebasan dari Amerika Latin dan juga black theology.86
Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pandangan itu pemberitaan Injil didasarkan pada dua sumber, yaitu Alkitab dan konteks. Menurut kami, pandangan itu harus ditolak berdasarkan keyakinan terhadap kuasa Alkitab. Jadi, jika hanya satu ungkap an yang digunakan, apakah kon tekstualisasi atau indigenisasi, timbul kesan bahwa Alkitab dan konteks sama-sama kuat dan saling memengaruhi.87
Satu alasan lain untuk tetap menggunakan konsep pengkristenan, yaitu bahwa dengan demikian gereja diharuskan memikirkan keadaan masyarakat secara menyeluruh, supaya Injil dapat meme ngaruhi masyarakat. Gereja terdorong untuk merumuskan peraturan-peraturan hidup yang adil adanya, dan yang juga menarik bagi orang yang bukan Kristen. Sebab, apa yang baik bagi seorang Kristen sebenarnya juga baik bagi tiap orang. Hukum Allah tepat dan sesuai untuk seluruh dunia. Sekalipun masa kristenisasi Eropa, yang dimulai pada abad Konstantinus Agung, sudah menjadi masa lalu, namun gereja dalam situasi yang misioner wajib untuk turut mengembangkan sebuah pola hidup yang bukan saja memberi nama baik bagi gereja, melainkan juga membangun masyarakat.
Bangsa Israel dan budayanya tidak selalu berbeda dari lingkungannya. Imamat 18:26 menyatakan bahwa di Israel, seorang pendatang pun terikat pada hukum-hukum perkawinan. Tuhan berkehendak agar hanya ada satu kaidah saja yang meng atur kehidupan masyarakat. Berarti, gereja Kristen terpanggil untuk memengaruhi masyarakat, agar mematuhi hukum Tuhan. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan senjata rohani. Karena perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru perlu dipedulikan.
Dalam masa Perjanjian Lama, hanya Israel yang merupakan bangsa Tuhan. Bahkan penduduk Kanaan perlu dibasmi, agar kebu rukan mereka tidak menjangkiti bangsa Israel (Im 18:24) dan juga karena kedurjanaan mereka sudah genap (Kej 15:16; Im 18:25). Tetapi, bila orang asing tinggal di tengah masyarakat Israel, mereka diwajibkan mengindahkan hukum Allah. Mereka juga ha rus diperlakukan sesuai dengan hukum itu. Rut, seorang perempuan dari Moab, bertobat kepada Allah Israel dan mempunyai hak di tengahtengah orang Israel (Rut 4:5).
Selain pengkristenan, dapat juga dirancang sebuah stra tegi yang berbeda, yaitu membentuk wilayah-wilayah yang dikhususkan untuk orang Kristen. Zending Gereformeerd menolak cara itu, dan menurut kami, hal itu benar adanya.88
Komunikasi antarbudaya
Dalam proses kontekstualisasi, seorang pemberita Injil ber usaha memperhatikan konteks. Sedangkan dalam proses peng kristenan, gereja muda yang telah terbentuk dan yang merupakan buah dari pemberitaan Injil, berusaha memenga ruhi masyarakat. Jadi, seorang pemberita Injil adalah pene rima dalam proses kontekstualisasi dan pengantar dalam proses kristenisasi. Tetapi, dalam hal ini kami mempunyai perbedaan tujuan dengan ilmu komunikasi modern, yang di dalamnya ilmu tersebut membedakan antara sumber (source), berita (message) dan penerima (receptor), sesuai dengan skema E.A. Nida yang sangat berpengaruh di bidang misiologi. Kerangka tersebut telah mendapat prioritas dalam buku C.H. Kraft; kemudian D.H. Hesselgrave mengutipnya dan menyetujuinya89.
Tiap proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan, begitu kata Nida, Kraft, dan Hesselgrave. Karena itu, isi berita sebagaimana yang diterima oleh pendengar, berbeda dengan berita sebagaimana yang keluar dari sumbernya. Yang lebih sulit lagi adalah komunikasi antarbudaya, seperti komunikasi berita Alkitab, yang berasal dari budaya lain.
Faktor-faktor yang berpengaruh adalah sebagai berikut:
- Dalam pembentukan Alkitab telah terjadi proses dengan sum ber, berita, dan penerima.
- Penerima dalam proses pertama, yaitu penulis Alkitab, telah menjadi sumber bagi kita pembaca Alkitab dalam abad ke-21. Jadi, mungkin saja kita menerima beritanya dalam pengertian yang dapat berbeda dengan arti semula.
- Dalam komunikasi Injil dari penginjil dunia Barat kepada orang yang berada di negara sedang berkembang, para zendeling menjadi sumber bagi mereka, tetapi ada kemungkinan mereka yang menerima beritanya meng artikan berita itu berbeda dengan pemberitanya. Konteks selalu berpengaruh dalam ketiga lingkungan ini: dunia penulis Alkitab, dunia Barat dan dunia ladang zending.
- Komplikasi terakhir adalah bahwa orang Kristen di gerejagereja muda itu bukan saja mendengar berita Alkitab dari para zendeling, melainkan mereka juga telah membaca Alkitab sendiri. Dengan demikian, mereka menjadi penerima langsung, yang mungkin memperoleh pemahaman berita yang berbeda dengan berita sebagai mana yang disampaikan oleh para zendeling.
Tentu pemahaman Alkitab bergantung pada pendengarnya sendiri, namun Alkitab tetap merupakan Firman Allah. Apa pun yang ditulis oleh para penulis, dan bagaimanapun pengaruh dari lingkungan mereka, Roh Allah selalu berkarya dalam tulisan mereka yang adalah Firman Tuhan, yang tidak mungkin keliru. Sean dai nya pembacanya salah mengerti maka pemahaman merekalah yang harus diperbaiki. Firman Allah berhadapan dengan ma nu sia, dan bukan di bawah manusia. Orang Kristen perlu saling menolong untuk lebih memahami kabar baik itu. Mereka saling mene rangkan, dan dalam hal itu memperhatikan perbedaan an tara dunia Alkitab dan dunia masa kini. Kepada penduduk Tanah Hijau perlu dijelaskan bagaimana bentuk seekor domba dan kepada orang Cina perlu dijelaskan bahwa dalam Alkitab seekor naga tidak melambangkan kuasa yang baik, seperti dalam alam pikiran mereka, tetapi kekuatan yang jahat. Tetapi bukan berarti pengertian tentang anak domba dalam Alkitab milik orang Tanah Hijau, dan dalam Alkitab orang Cina tentang ular naga dihilangkan (contoh-contoh tersebut sudah tua). Berita Alkitab, yaitu ”ajaran” tidak boleh diubah, tetapi perlu dijelaskan, dan khususnya di bagian-bagian yang mudah terjadi kesalahpahaman. Itulah kontekstualisasi.
Kontekstualisasi, tetapi bukan mengenai ajaran
Bagi kami, kontekstualisasi bukan saja penafsiran yang tepat, yang menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh konteks para pendengar, melainkan juga menghiraukan konteks dalam liturgi, tata gereja, dan etika. Tanpa kontekstualisasi di bidang-bidang tersebut, akan mudah terjadi bagian dari ke budayaan dan kebiasaan dari para zendeling dialihkan seolah-olah itu adalah pesan Alkitab.90
Memang, ajaran dan praktik kehidupan tak dapat dipisahkan, namun perlu dibedakan. Plaisier mengatakan bahwa di Tana Toraja para zendeling gagal dalam bidang komunikasi, yang di dalamnya pemberitaan tidak dikontekstualisasikan. Tetapi, menu rutnya, di bidang budaya dan etika sosial mereka berhasil dalam kontekstua lisasi menyebabkan Gereja Toraja menjadi sebuah gereja yang benar-benar pribumi sifatnya.91 Pengalaman Plaisier mendukung pandangan kami bahwa perlu dibedakan antara kontekstualisasi dalam ajaran dan praktik kehidupan.
Tentu, di Tana Toraja gereja juga bergumul, apakah agama penyembah berhala dapat dipandang terlepas dari ke biasaan-kebiasaan di dalamnya. Sebab, mereka juga menyadari bahwa agama telah memengaruhi segala sesuatu, tetapi tidak semuanya yang tergolong dalam ibadat berhala dan sering dapat diartikan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam kafir. H. Van der Veen, seorang ahli bahasa yang sejiwa dengan Kruyt dan Adriani, yang mempunyai pengalaman yang lama sekali di Zending GZB, membedakan aluk (agama, pandangan dunia) dan adat (kebiasaan).92 Perlu diakui bahwa adat termasuk aluk, seperti yang diamati oleh antropolog-antropolog, dan oleh orang Toraja sendiri, dan dipahami juga oleh para zendeling. Tetapi, untuk memupuk pertumbuhan Injil tidak mungkin setiap kebiasaan dan budaya dihilangkan lebih dahulu,
sebab manusia tidak dapat memulainya tanpa mempunyai pegangan sama sekali.
Satu sumber, bukan dua sumber
Bruce J. Nicholls dan George W. Peters adalah misiolog yang setia pada Alkitab dan yang telah mendefinisikan kontekstualisasi dari sudut pandang mereka pada tahun tujuh puluhan. Mereka hanya fokus pada komunikasi verbal dan tidak peduli terhadap ibadat, tata gereja, dan etika.93 Menurut Nicholls, kontekstualisasi adalah ”penerjemahan isi Injil Kerajaan yang tidak berubah ke dalam bentuk lisan yang bermakna bagi bangsa-bangsa dalam budaya mereka dan dalam situasi-situasi eksistensial mereka”. Menurut Peters, maksud dari kontekstualisasi yang diterapkan adalah ”menemukan implikasiimplikasi yang sah dari Injil dalam suatu situasi tertentu. Ini lebih dalam daripada hanya penerapan. Penerapan dapat dibuat atau tidak dibuat, dan teks tetap sama. Tetapi, implikasi-implikasi dituntut oleh tafsiran teks yang tepat.”94
Mereka dan juga conservative evangelicals (kata Hesselgrave/
Rommen) yang lainnya tidak hendak menolak ungkapan kontekstualisasi atas dasar suasana kritik Alkitab yang dibawanya. Mereka menyukai ungkapan tersebut dan mendefinisikan pandangan mereka sendiri, alih-alih menolaknya total.
Hesselgrave dan Rommen menunjukkan bahwa peman faatan ungkapan tersebut memang bermacam-macam, dari liberal sampai ortodoks. Dalam sumbangan-sumbangan dari aliran liberal, banyak konteks yang diperhatikan, dan hanya sedikit yang diambil dari penyataan Alkitab, sedang dari aliran ortodoks justru banyak penyataan Alkitab dan hanya sedikit yang menyangkut konteks.95
Akan tetapi, menurut Hesselgrave dan Rommen, perbe daan antara liberal dan ortodoks adalah perbedaan yang tidak mutlak, padahal menurut kami hal itu mutlak. Titik perbedaan adalah kesungguhan kepercayaan pada penyataan Alkitab. Bagi mereka, terdapat dua sumber, yang daripadanya masing-masing menimba banyak atau sedikit saja, tetapi kami meyakini yang ada hanya satu sumber. Konteks menyampaikan materi untuk penafsiran Alkitab.
S.B. Bevans melukiskan lima pola kontekstualisasi, antara lain ’translation-model’ yang ortodoks, misalnya oleh Hesselgrave,
dan juga model liberal yang antropologis. Model yang pertama mene kankan pengaruh Injil pada budaya dan model kedua justru sebaliknya.96
Kami menyadari bahwa pandangan kami sendiri mirip dengan pandangan antropologis dalam uraian Bevans, kare na memberi perhatian pada pengaruh pola masyarakat atas pemberitaan dan justru itu yang selalu ditekankan oleh antropologi. Namun, pan dangan kami berbeda dengan model antropologis yang dikemu kakan Bevans, yang di dalamnya ditentukan oleh konteks. Dalam pandangan kami, Alkitablah yang berkuasa.
Istilah-istilah populer perlu dimanfaatkan dengan baik
Pengkristenan maupun kontekstualisasi dapat digunakan sebagai ungkapan yang berguna, tetapi perlu didefinisikan dengan baik. Peng kristenan sebagai strategi untuk pertobatan bangsa secara massal kami tolak.97 Pengkristenan bukan alat untuk pertumbuhan gereja, melainkan tugas yang harus dilakukan oleh gereja yang telah bertumbuh oleh Roh dan Firman. Jadi, kami memilih memakai kedua istilah secara bersama: kontekstualisasi dan kristenisasi, sebagai dua gerakan yang berbeda dalam satu proses. Keduanya sering digunakan secara sinonim, tetapi hal itu berakibat pada tercampurnya Alkitab dan konteks. Bila dibedakan antara satu dan yang lain, maka yang satu bergerak menuju Firman (kontekstualisasi) dan yang lain bergerak dari Firman ke lingkungan (kristenisasi).
Kami lebih menyukai istilah ”kontekstualisasi” dibandingkan dengan
- Accomodatio, ungkapan lama dari Gereja Katolik Roma, yang mengesankan bahwa pendekatan misioner akan berhasil bila keagungan dan ”ketuhanan” Firman dikurangi. Sebab, konon, gaya Firman tidak langsung sesuai karena keagungannya. Padahal Firman Tuhan bermanfaat dan memang dapat diterapkan.
- Possessio, ungkapan yang disukai oleh J.H. Bavinck. Benar bahwa Kristus berhak memiliki (possessio: memiliki) seluruh hidup, tetapi tekanan atas ”klaim” tersebut membuat ungkapan tersebut dirasakan memaksa. Mengesankan juga bahwa dunia ini milik Iblis dan perlu dimenangkan kembali. Sekalipun Iblis memang mempunyai kuasa, namun menurut Wahyu 20 dia telah dikalahkan dan telah diikat. Kristus adalah Raja.
- ”Inkarnasi”, istilah yang lazim dalam teologi modern. Hanya ungkapan ini tetap dikhususkan bagi kedatangan Anak Allah menjadi manusia. Malah justru merekalah yang menyebutnya untuk menunjukkan bagaimana berita Injil masuk ke dalam lingkungan, mereka juga yang sering menyangkal bahwa Anak Allah telah menjadi manusia.
- ”Inkulturasi” juga kurang tepat, karena tidak seharusnya budaya (kultur) tumbuh karena Firman yang ditanam di dalamnya. Unsur budaya yang baik perlu dimanfaatkan demi pemberitaan Firman. Firman yang harus tumbuh.
- ”Indigenisasi” perlu ditolak, karena hal yang ”indigen”/pribumi itu tidak perlu dimunculkan.
- Ungkapan seperti ”rekulturasi”, ”transformasi” atau ”metamor fosa” bukan perbaikan. Istilah-istilah itu maupun istilah kris tenisasi bertujuan sama, tetapi kristenisasi adalah satu istilah yang mengandung kata ”Kristen” di dalamnya, sedangkan yang lain tidak. Demikian juga istilah-istilah tersebut tidak memper hatikan secara khusus pengaruh konteks dalam pemberitaan Injil.
Kami memilih kontekstualisasi asal dikaitkan dengan pengkris tenan, karena ungkapan itu sudah biasa digunakan. Terutama juga karena ungkapan itu berbeda dengan yang sebelumnya, dapat menunjukkan gerakan dari lingkungan ke Firman, dan bukan hanya gerakan dari Firman ke budaya. Yang terakhir itu menurut kami lebih tepat disebut pengkristenan, karena kontekstualisasi memang harus disusul oleh pengkristenan, karena seluruh dunia perlu mengenal Kristus dan mengakui-Nya, agar dunia hidup.
4. Pemanfaatan Alkitab dalam Etika
Dalam bagian 4.3 kami membedakan antara kontekstualisasi mengenai ajaran, yang kami tolak, dan kontekstualisasi dalam tata gereja, tata ibadat, dan etika, yang kami anggap perlu. Mungkin kata
”ajaran” menimbulkan kesan yang tidak baik, yaitu intelektual, tetapi kami teringat pada perkataan-perkataan Paulus kepada Timotius dan Titus tentang ”ajaran yang sehat” yang perlu dipertahankan dan diberitakan, dan betapa seringnya muncul istilah ”ajaran” dalam surat-surat itu. Hanya saja ”ajaran” di satu sisi dan tata gereja, tata ibadat dan etika di sisi lain, tidak dapat dipisahkan secara mutlak.
Dengan pembedaan tersebut kami berharap akan terca pai suatu hasil yang baik dan yang sama dengan pembedaan lama antara norma normans (norma pengukur, yaitu Alkitab) dan norma normata (norma ukuran, yaitu yang diukur oleh Alkitab), yang berlaku dalam kehidupan nyata. Kedua norma-norma itu ditemukan juga dalam Alkitab, yang dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama, antara lain misalnya tentang sunat dan mohar. Kedua peraturan itu tidak perlu diterapkan sampai sekarang, namun kebiasaan-kebiasaan itu berlandaskan data-data yang tetap berlaku: sunat berlandaskan perjanjian Allah dengan bangsa-Nya dan mohar berlan daskan pengaturan perkawinan yang sah.
Seorang filsuf Reformed dari Belanda, S. Griffioen, menge mukakan hal yang sama. Dia mengutip filsafat yang dise but Wijsbegeerte der Wetsidee (filsafat yang didasarkan pada lingkungan-lingkungan hukum). Perintis-perintisnya adalah Dooyeweerd dan Vollenhoven. Filsafat itu membedakan antara hukum dan norma, yaitu antara dasar hukum dan penerapan hukum. Mengikuti filsafat itu, Griffioen menen tang Kraft yang membedakan antara unsur budaya dan unsur suprabudaya.98 Maksud Griffioen adalah bahwa manusia harus mengambil keputusan-keputusan secara bertanggung jawab atas segala tingkat. Tanggapan terhadap hal-hal yang konkret tidak boleh dianggap remeh, sedangkan tanggapan terhadap norma universal dianggap serius, karena justru nor ma universal itu selalu perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh.
Oleh karena itu, perlu dicari apa yang termasuk ”ajaran” dan apa yang termasuk ”praktik hidup”, atau apa yang termasuk norma normans dan apa yang termasuk norma normata, apa yang asasi dan apa yang sifatnya penerapan. Dalam Alkitab kedua hal itu bercampur. Dan kepu tusan yang baik dapat diambil berdasarkan tafsiran yang dalam dan pengetahun tentang sejarah penyataan Allah.
J. Douma menerangkan hal itu secara konkret dengan menyebut empat fungsi Alkitab: sebagai pemandu, sebagai penjaga, untuk menunjuk jalan, dan untuk memberi teladan.99
Sebagai pemandu, Alkitab berperan baik yang menyangkut ajaran, maupun mengenai praktik kehidupan. Dalam banyak hal Alkitab sung guh sangat jelas, dalam dogmatika maupun etika terdapat loca probantia (nas-nas pembukti), misalnya: relasi laki-laki dan perempuan. Meskipun banyak perubahan secara praktis, sehubungan dengan emansipasi perempuan, namun relasi tersebut tetap berlandaskan karya Allah Pen cipta yang telah mengaturnya dari semula bahwa laki-laki adalah kepala, bandingkan ajaran Paulus tentang hal itu dalam Efesus 5.
Sebagai penjaga, Alkitab berperan dalam kasus-kasus yang di dalamnya tidak dapat ditemukan satu petunjuk langsung dari Firman Tuhan, karena perbedaan waktu dan budaya. Misalnya, dengan tegas Alkitab melarang menghina Allah atau menin das sesama manusia, dan peringatan itu perlu diindahkan dalam ber bagai situasi. Banyak contoh dalam Alkitab yang mengajarkan betapa seriusnya Allah meng hukum penghinaan dan penindasan.
Untuk menunjukkan jalan, maka Firman Tuhan memper lihatkan kepada manusia faktor-faktor yang tetap ada dan yang juga berlaku sampai sekarang. Misalnya secara tidak langsung ditemukan dalam Alkitab tentang bayi tabung, manusia perlu dibimbing oleh hukum yang keenam, untuk tidak membuang sekian banyak cikal bakal embrio demi memelihara yang satu saja.
Alkitab juga memberi banyak teladan yang menolong jemaat di masa kini, khususnya teladan yang Yesus lakukan.
Kuasa Alkitab
Menerima Alkitab sebagai Firman Allah tidak berlawanan dengan pembedaan antara norma normans dan norma nor mata. Bukan segala sesuatu yang dibaca dalam Alkitab adalah norma normans, melainkan, jika Alkitab dianggap firman manusia dan bukan Firman Allah maka tidak ada lagi norma normans yang tertinggal, dan seluruh isi Alkitab dianggap relatif dan tergantung dari waktu dan kondisi.
Luther dan Calvin serta sekian banyak penjelasan katek is mus yang diterbitkan sesudahnya, meyakini kebenaran bahwa dalam perkara-perkara etis, Alkitab merupakan penunjuk jalan. Akan tetapi, eksegese yang disebut historis-kritis justru menyangkal pemanfaatan Alkitab itu. Filsafat eksistensialis juga berpengaruh, dengan menyangkal adanya kebenaran-kebenaran yang tetap ber laku, misalnya teologi Karl Barth. Tetapi, Barth dalam hal-hal tertentu juga dengan sangat jelas merumuskan peraturan-per aturan etis yang baik hingga Douma berkesimpulan bahwa Barth adalah seorang teolog yang tidak lagi menggunakan cara peman faatan Alkitab yang klasik, namun sekaligus memaparkan peraturan-peraturan yang ham pir sama dengan peraturan yang biasanya ditolak oleh banyak orang karena dianggap alkitabiah.
Biblisisme berarti bahwa nas-nas Alkitab dipisahkan dari konteks kalimat, dan kadang-kadang juga dari konteks Alkitab sebagai keseluruh an. Juga sering terjadi, teolog yang menolak Alkitab sebagai Firman Allah yang berkuasa malah memegang satu motif dari Alkitab sebagai intinya, misalnya pelepasan, atau kasih. Douma bertanya, apa hak seseorang memilih tema-tema tertentu dan menghubungkannya dengan nama Tuhan, sedangkan dia tidak menerima Alkitab secara ke seluruhan.
Teolog seperti H.M. Kuitert menyadari bahwa tiap keputusan ten tang apa yang penting dan tidak dalam Alkitab benar-benar ber landaskan ”titik tolak budaya” yang dipegangnya (pra sangka).
Karena itu, Kuitert menolak tiap penanggungan jawab etis atas dasar Alkitab. Douma memang menyetujui bahwa ada prasangka pada tiap orang yang mengambil keputusan etis, tetapi selanjut nya dia juga mengatakan bahwa iman/percaya kepada kebenaran Firman Allah bukan sebuah prasangka yang berlandaskan titik tolak budaya. Itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus.
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
Nas-nas Alkitab yang dibahas dalam Bab 3 sebagian besar berasal dari Kitab Perjanjian Lama. Hal itu tidak berarti bahwa nas-nas tersebut tidak berlaku lagi. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya bukan meniadakannya, melainkan mengge napinya.
Teologi Reformed sejak semula membedakan hukum moral, hukum seremonial (upacara) dan hukum sipil (kenega raan). Memang tidak mungkin memisahkannya dengan jelas, tetapi membedakan ketiga segi hukum tersebut sangat penting. Hukum-hukum moral tetap berlaku, sebagaimana ditekankan Kristus dalam Khotbah di Bukit (Mat 5-7). Dengan demikian, hukum mencapai tujuannya. Tetapi, hukum yang menyangkut ibadat dan upacara Perjanjian Lama juga telah mencapai tujuannya, tetapi secara berbeda, yaitu bukan dengan mengikatkan, melainkan dengan menunjuk kepada Kristus yang telah melaksanakan segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Karena itu, hukum ibadat itu merupakan ajaran bagi jemaat di masa kini (Pengakuan Iman Belanda, 1561, ps 25). Demikian juga, hukum-hukum sipil Perjanjian Lama tidak lagi berlaku sebagai hukum sipil untuk kita pada masa kini, namun tetap mengandung ajaran dan secara tidak langsung mengatakan bahwa gereja Tuhan pada masa kini tidak lagi dijumpai hanya pada satu bangsa secara khusus (bangsa Israel pada Perjanjian Lama) tetapi dapat dijumpai di seluruh bumi.
Pengkristenan yang kami anjurkan di atas, tidak boleh dimaksudkan untuk menegakkan satu teokrasi sebagaimana di Israel, seandainya pun hal itu mungkin. Di mana pun juga, antara gereja dan negara perlu dipisahkan. Iman tidak boleh dipaksakan.
5. Kebutuhan Kontekstualisasi dan Kristenisasi di Sumba
Sekitar pem-belis-an
Pada masa lalu, ketika di beberapa daerah budaya pem-belis-an dilarang total, telah menimbulkan berbagai masalah yang memberatkan masyarakat karena penyerahan perempuan mengikat suatu kekerabatan sosial. Hal ini yang menjadi salah satu alasan untuk tidak menghilangkannya. Apakah di samping itu juga terdapat nilai positif untuk mempertahankannya? Apakah diteruskannya adat pem-belis-an akan mendukung penerimaan Injil oleh masyarakat? Menurut kami ya!
Dengan demikian, Injil benar-benar dilihat sebagai berita bagi orang Sumba. Mereka tidak perlu mengubah seluruh pola ke hi dupan mereka.
Injil mengindahkan hubungan keluarga, hal itu berharga demi untuk pembangunan jemaat dan pendidikan generasi muda di jemaat. Bila keluarga baru diterima dengan baik oleh ke dua pihak keluarga maka perkembangannya lebih bagus, demikian juga ditinjau dari segi kekristenan. Di sini terdapat analogi dengan cara pemerintahan gerejawi, karena akan menguntungkan jika dalam membentuk struktur jemaat, suatu pola kepemimpinan yang sudah dikenal dapat diteruskan.
Injil tidak berlawanan dengan persiapan perkawinan yang bertahap, bahkan tata cara seperti itu akan menguntungkan. Jadi, dalam hal ini jemaat dapat mengikuti cara pengurusan perkawinan adat Sumba yang klasik.
Etika Kristen mendorong agar tiap perkawinan diteguhkan secara resmi di depan umum, melalui pencatatan sipil. Di sini letak kemiripannya dengan adat Sumba yang lama, karena pengesahan oleh kedua keluarga besar membuat perkawinan tersebut diakui secara umum.
Jemaat Kristen akan berkembang jika terjadi konfrontasi/per tentangan antara Injil dan inti agama marapu, tetapi per kem bangannya akan terhambat jika terjadi pertentangan dalam pokok-pokok seperti pem-belis-an.
Untuk mewarnai kehidupan pribadi dan kehidupan ge rejawi, dapat saja manusia menimba dari konteksnya (ling kungan hidupnya). Jadi, termasuk juga untuk pemikiran dan tindakan etis, termasuk etika perkawinan. Pengkristenan akan berhasil bila ajaran gereja tidak disesuaikan dengan konteks, karena berita yang harus dibawa adalah Injil, yang dikabarkan oleh gereja yang kudus dan am, yang meng harapkan keselamatan dari Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan, pelepasan, dan penciptaan kembali.
Sekitar perkawinan
GGRI di Sumba mempunyai dua dokumen yang digunakan dalam liturgi perkawinan gerejawi, dan yang pertama berasal dari gereja induk di Barat.100 Dokumen itu adalah Formulir untuk Nikah Suci, yang merupakan terjemahan formulir yang berlaku dalam Gerejagereja Reformed (GKV, Liberated Churches) di negeri Belanda sejak tahun 1975101. Formulir ini diikuti dalam ibadah perkawinan mereka yang tidak melakukan ”kawin duduk”. Akan tetapi, formulir ini tidak sering dipakai. Dalam kebanyakan kasus orang meng gunakan dokumen yang kedua, yaitu formulir pendek, yang konon disusun pada akhir tahun 1930-an oleh pendeta-pendeta misioner. Pada dasarnya formulir ini merupakan rumus pengakuan dosa oleh mereka yang telah melakukan ”kawin duduk” dan kini ingin melangsungkan perkawinan resmi. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kenyataannya hidup serumah di luar nikah, seperti yang berlaku di Sumba, berbeda dengan pengertian tentang hidup serumah yang banyak ditemukan di negara-negara Barat. Dalam masya rakat Barat kebiasaan tersebut timbul disebabkan pengaruh pemikiran individualisme, sedangkan di Indonesia gejala tersebut disebabkan oleh tuntutan dari keluarga masing-masing, yang berakibat perkawinan ditunda-tunda, sedangkan pada dasarnya persetujuan keluarga, gereja, dan negara tetap diinginkan. Di Sumba dikatakan bahwa yang bersangkutan belum menikah sebab ”adat belum selesai”, artinya: ”belis belum dibayar”.
Apa pun penilaian kita terhadap sifat ”kawin duduk” itu, para zendeling beranggapan bahwa mereka yang hidup serumah di luar nikah harus mengaku dosa lebih dahulu, baru dapat menikah dengan resmi, seperti yang juga terjadi di gereja asal mereka pada waktu itu. Tetapi, para utusan tersebut tidak memperhatikan perbedaan Sumba dengan Barat yang kami singgung tadi. Akibatnya, formulir pengakuan dosa tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, tetapi menjadi pilih an yang kedua bila formulir nikah suci dianggap tidak boleh digunakan. ”Formulir Pengakuan Dosa Orang yang Kawin Duduk”, sering disebut ”Formulir Perbaikan Nikah”.
Demikianlah jalan yang ditempuh oleh Zending untuk menampung keadaan yang telah timbul akibat pem-belis-an. Untuk memungkinkan orang yang bersalah karena ”kawin duduk” meni kah secara gerejawi, Zending merancangkan formulir baru, yang di kemudian hari diambil alih oleh gereja. Akan tetapi, kita dapat bertanya: Apakah jalan keluar itu memang jalan yang tepat? Apakah dengan cara ini masalah pem-belis-an diselesaikan secara seimbang dan adil? Zending memandang pemberlakuan formulir pengakuan dosa sebagai upaya kontekstualisasi, tetapi kurang memperhatikan bahwa upaya itu justru menutup jalan ke arah kristenisasi. Para zendeling ingin mengkristenkan pola hidup bermasyarakat, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya; struktur masyarakat menyebabkan perubahan hasil formulir. Hal itu dapat dilihat pada nama populer formulir tersebut: ”Formulir pengakuan dosa” yang dalam praktiknya menjadi jalan pintas menuju perkawinan, yaitu melalui ”perbaikan” hubungan yang sudah ada. Maka dalam Bab 5 kami menganjurkan penghapusan formulir pengakuan dosa itu. Anjuran itu diterima oleh Seminar GGRI tahun 2003.
Kami yakin bahwa formulir yang disebut pada awal bagian ini ber fungsi baik pada tiap perkawinan gerejawi, termasuk perkawinan mereka yang telah ”kawin duduk”. Memang strukturnya dapat tetap dipertahankan, namun bentuknya perlu diubah dan dise suaikan.
Khususnya dalam bagian formulir yang membicarakan penetapan nikah, seharusnya juga diberi keterangan tentang perbe daan antara perintah-perintah alkitabiah berkenaan dengan perkawinan dan pandangan masyarakat Sumba tradisional.
Catatan kaki
tentang sejarah Gereja Kristen Sumba 1859-1972, hlm 351, 352.
a.w., hlm 156. Barangkali yang dimaksudkan dengan ”nama baru” itu kutipan dari Wahyu 2. 1993, hlm 645.
wij”, dan: ”De weerbarstige werkelijkheid”. zending tentang sejarah Gereja Kristen Sumba 1859-1972, hlm 290, 291.
”Pada bulan-bulan itu ia menghabiskan waktu untuk menjual seorang anak saudara, yang baru berumur 4,5 tahun, sesuai peraturan adat. Ia berusaha mendapatkan uang itu dan sedang mengurus juga pertunangannya sendiri, juga sesuai adat”.
- kebiasaan itu adalah adat kekafiran Sumba,
- kebiasaan itu menindas kebebasan laki-laki/perempuan,
- barang-barang yang bersifat jasmaniah tidak berkuasa untuk meng ikat hubungan cinta.
Allah adanya, diindahkan oleh segala anggota sidang, sehinggaanggota-anggota sidang tidak mengurus nikah lagi cara kafir (dengan ’kasih masuk sirih-pinang’ atau dengan ’belis’), melainkan hanyalah cara Kristen. Cara Kristen ialah mengindahkan aturan-aturan pemerintah, yang berhak akan melangsungkan nikah-nikah sehingga sah. Sedangkan pemerintah telah memberi hak kepada gereja-gereja akan melangsungkan dan mene guhkan nikah-nikah, maka segala anggota sidang tidak boleh mencari jalan lain lagi akan melangsungkan atau mengesahkan nikah. Nikah-nikah yang dilangsungkan cara resmi oleh pegawai pemerintah dapat diteguhkan didalam gereja, jikalau dua pengantin itu anggota gereja, yang tidak memberi syak. Nikah-nikah yang diurus cara kafir (dengan ’kasih masuk sirih pinang’ atau dengan ’belis’) tak dapat diteguhkan dalam gereja. Sebab nikah itu aturan Allah adanya, dan bukan permainan, yang lebih dahulu cara kafir dan sesudah itu cara kristen dapat dilangsungkan.”
Yang menjadi persyaratan bagi perkawinan gerejawi adalah bahwa kedua mempelai merupakan anggota gereja dan belum hidup serumah. Sayang, yang terjadi biasanya ”kawin duduk” dahulu, baru kemudian pengakuan iman diikrarkan sekaligus pengakuan dosa. Adakalanya sekaligus dengan pembaptisan anak.
Informasi Buku
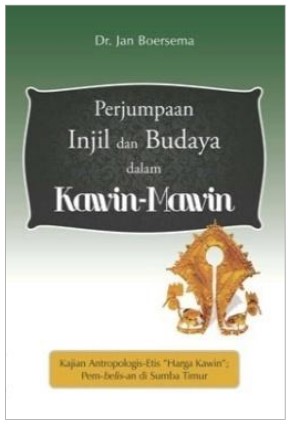 PDF
PDF
- Penulis:
J.A. Boersema - ISBN:
978-602-1006-04-7 - Copyright:
© 2015, Jan Boersema - Penerbit:
Yayasan Komunikasi Bina Kasih